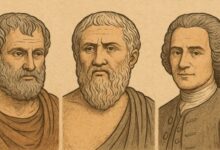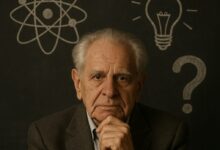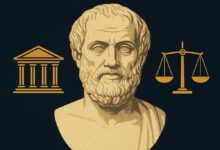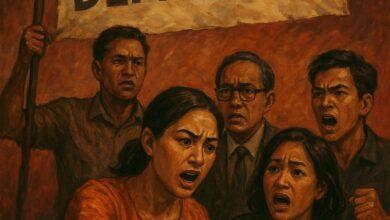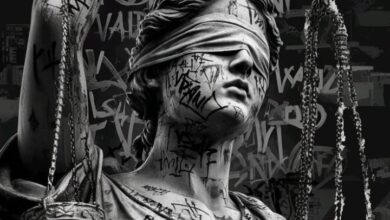Demokrasi Indonesia dalam Perspektif Filsafat Hukum
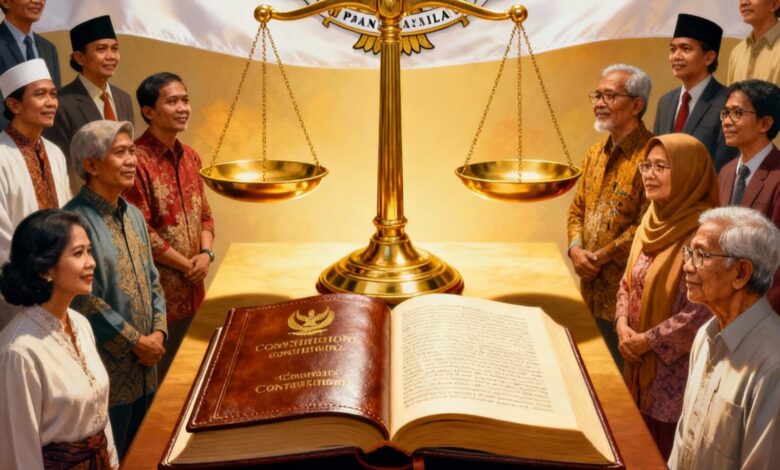
ZETIZENS.ID – Menurut saya, demokrasi Indonesia masih menyimpan paradoks yang cukup serius. Di satu sisi, masyarakat telah diberikan kemampuan untuk mengekspresikan pendapat mereka melalui pemilihan umum, forum, serta jajak pendapat.
Di sisi lain, suara rakyat sering kali tidak diterjemahkan dengan akurat menjadi kebijakan yang melayani kepentingan bersama. Dalam artikel Jajak Pendapat sebagai Ekspresi Pendapat Publik, Pilar Kelima Demokrasi? (Adiputra, 2008), dinyatakan bahwa opini publik seharusnya menjadi “pilar kelima demokrasi,” menambah eksekutif, legislatif, yudikatif, dan pers.
Komunikasi politik di Indonesia masih sangat kurang melibatkan rakyat. Jajak pendapat dan survei yang seharusnya menjadi instrumen untuk menangkap suara rakyat cenderung berfungsi sebagai instrumen untuk melegitimasi politik para elit.
Dari sisi sejarah, hal ini yang bisa dipahami, Socrates misalnya menekankan pentingnya diskusi terbuka dalam upaya meneguhkan kebenaran.
Menerjemahkan sudut pandangnya, demokrasi seharusnya disertai dengan ruang pemikiran. Pembicaraan dalam demokrasi di negara kita kenyataan lebih banyak berupa pengumpulan angka asal.
Musyawarah dalam Republik Indonesia, demokrasi, lebih banyak fetis dari dalamnya. Ini membuktikan bahwa di Indonesia, publikasi lebih banyak bersifat simbolis. Jika saja prinsip dialog Socrates diimplementasikan, demokrasi kita bertentangan dengan ruang publik yang sekarat, arena berpikir disesaki ide, rakyat diajak membentuk argumentasi pada kajian keputusan.
Cicero, pemikir, politikus juga seorang Romawi, memberikan pandangan yang relevan untuk gagasan yang kita diskusikan. Ia memberikan perhatian tersendiri pada hukum alam, yang juga disebut akal budi, prinsip keadilan yang dipegang oleh masyarakat tanpa melihat status sosial dan kekuasaan.
Melekat dengan Indonesia seharusnya, dengan polling, opini pers warga dengan cara yang menekan sistem untuk bekerja lebih adil. Hukum di Indonesia tidak mencerminkan aspirasi rakyat.
Terlalu banyak yang lembek terhadap ikan besar kejahatan-korupsi, terlalu banyak orang yang diperlakukan buruk karena kesalahan kecil.
Menurut saya, ini menjadi kasus yang menunjukkan bahwa dukungan masyarakat yang hendak menuntut keadilan masih sanggup dicapai, tetapi tidak berpengaruh dalam proses penegakan hukum di negara kita.
Dari kacamata Cicero, hukum di negara ini gagal mematuhi batas-batas yang seharusnya menjadi dasar hukum dalam penegakan suatu supremasi moral dan rasional. Dengan logika lain, hukum itu lebih bersifat sebagai instrumen pembenaran kekuasaan suatu elite, bukan hasil dari keinginan masyarakat banyak.
Pandangan lain yang tidak kalah penting ditambahkan oleh John Locke. Dalam Two Treatises of Government, Locke berpendapat bahwa setiap pemerintahan yang sah harus dibangun di atas kesepakatan dalam masyarakat dan harus menjamin hak-hak dasar, di antaranya hak untuk hidup, hak atas kebebasan, dan hak atas milik.
Dari pandangan saya, ini adalah inti daripada demokrasi di dalam tatanan pemerintahan modern yang hingga saat ini masih relevan. Namun berlawanan, di Indonesia ada banyak kebijakan publik yang tidak selaras dengan kehendak mayoritas masyarakat.
Misalnya, dalam pengelolaan sumber daya alam, pemerintah sering kali lebih melindungi kepentingan investor besar dibanding masyarakat yang terkena dampak. Memang ada survei dan polling yang hasilnya menunjukkan dukungan terhadap kebijakan tertentu, tetapi umumnya dukungan itu lebih banyak dibangun dari pengaruh media, kampanye elit, dan kepentingan kelompok tertentu daripada asumsi murni masyarakat.
Dengan demikian, demokrasi yang kita anut, ditinjau dari bunyi ketentuan yang dibuat oleh Locke, adalah mengada-ada.
Masalah lain yang membuat demokrasi Indonesia semakin rapuh adalah rendahnya literasi politik masyarakat. Banyak warga masih mudah dipengaruhi oleh opini populer atau hasil polling yang ditampilkan media tanpa memeriksa metodologi dan sumbernya.
Akibatnya, opini publik rentan sekali dijadikan alat propaganda politik. Situasi ini membuat saya melihat bahwa kritik klasik Plato tentang bahaya kebebasan tanpa pengetahuan tetap relevan, meskipun ia bukan filsuf utama yang saya refleksikan di sini.
Demokrasi membutuhkan rakyat yang rasional dan kritis, bukan rakyat yang mudah digiring opini. Tanpa itu, opini publik akan terus dimanipulasi oleh kepentingan jangka pendek.
Selain itu, menurut saya, peran media massa dan media sosial juga sangat menentukan dalam memperkuat atau justru melemahkan fungsi opini publik.
Media yang sehat seharusnya menjadi sarana pendidikan politik rakyat, memberi informasi yang benar, dan menyalurkan aspirasi masyarakat secara objektif. Akan tetapi, kenyataannya banyak media cenderung berpihak pada kepentingan tertentu, sehingga hasil polling atau survei sering diberitakan dengan framing yang tidak netral.
Kondisi ini membuat opini publik semakin rentan dimanipulasi. Jika media dapat dikelola dengan prinsip transparansi dan profesionalitas, maka opini publik sebagai pilar kelima demokrasi bisa lebih kokoh dan dipercaya oleh masyarakat luas.
Menurut saya, solusi dari persoalan ini terletak pada dua hal penting. Pertama, lembaga survei dan polling harus diperkuat agar benar-benar independen, transparan, dan akuntabel. Hasil survei tidak boleh hanya menjadi pesanan elite, melainkan harus merefleksikan suara rakyat yang sebenarnya.
Kedua, literasi politik masyarakat harus ditingkatkan melalui pendidikan dan informasi yang berkualitas. Rakyat perlu belajar untuk menilai data, mempertanyakan hasil polling, dan tidak mudah menerima informasi mentah-mentah. Dengan begitu, opini publik dapat menjadi kekuatan moral sekaligus kontrol sosial yang nyata bagi jalannya demokrasi.
Oleh karena itu, menurut saya, demokrasi Indonesia masih membutuhkan kerja keras untuk mewujudkan cita-cita yang sesungguhnya.
Rakyat harus diberi ruang untuk berdialog secara kritis, hukum harus berpihak pada keadilan universal, dan pemerintahan harus selalu berdiri di atas persetujuan rakyat.
Semua ini hanya bisa terwujud bila opini publik ditempatkan sebagai kekuatan moral yang independen, bukan sekadar instrumen politik praktis. Dengan demikian, demokrasi kita tidak hanya berjalan dalam kerangka prosedural, melainkan berkembang menjadi demokrasi substantif yang benar-benar menyejahterakan rakyat dan menjaga martabat bangsa.
Akhirnya, refleksi filsuf klasik memberi kita arah penting. Socrates mengingatkan kita agar membangun ruang dialog yang hidup, Cicero menekankan bahwa hukum harus berdiri di atas prinsip keadilan universal, dan Locke menegaskan pentingnya persetujuan rakyat sebagai fondasi pemerintahan.
Jika gagasan-gagasan ini dipadukan dengan kritik Adiputra (2008) tentang lemahnya peran opini publik, maka demokrasi Indonesia dapat keluar dari jebakan formalitas.
Polling tidak lagi hanya menjadi angka di atas kertas, melainkan cerminan nyata dari aspirasi rakyat yang dihormati. Menurut saya, demokrasi Indonesia baru akan menemukan rohnya ketika opini publik tidak hanya dihitung, tetapi juga dihargai, didengarkan, dan diwujudkan dalam kebijakan yang adil. (*)
Ditulis oleh Umi Nasroh Muyassaroh, mahasiswi Unpam