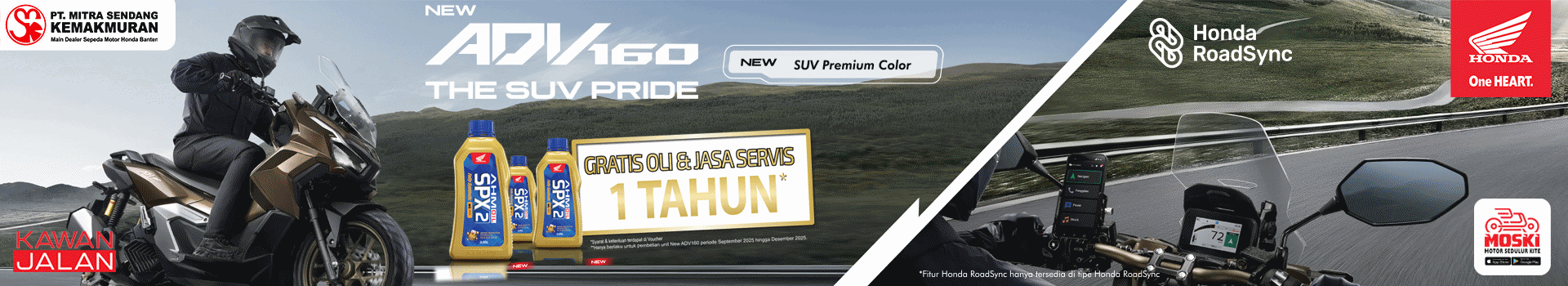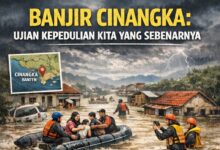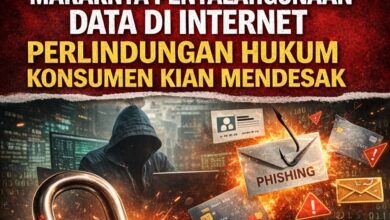Oligarki, Politik Uang, dan Krisis Kaderisasi: Potret Buram Partai Politik Kita
Oligarki Internal Partai: Kekuasaan Elit yang Menguat

ZETIZENS.ID – Fenomena oligarki menjadi wajah buram partai politik di Indonesia. Mekanisme demokratis yang seharusnya membuka ruang partisipasi kader sering tersumbat oleh dominasi elit yang memegang kendali penuh atas struktur dan keputusan partai.
Proses seleksi calon legislatif maupun kepala daerah kerap dipengaruhi faktor koneksi, loyalitas personal, serta kemampuan finansial, bukan kapabilitas atau rekam jejak publik.
Studi pada kaderisasi PDI-P di Kabupaten Garut menunjukkan lemahnya tindak lanjut pasca pelatihan dan minimnya monitoring terhadap kader di lapangan, sehingga menghasilkan kader loyal tetapi kurang mumpuni. Hal ini memperkuat oligarki karena keputusan tetap berpusat pada elit partai, bukan basis kader.
Akibatnya, lahirlah fenomena “partai keluarga” atau “partai patronase” di mana jabatan strategis diwariskan kepada lingkaran dekat elit.
Pola ini memperkuat oligarki internal dan melemahkan demokrasi internal partai. Penelitian yang dilakukan oleh berbagai akademisi menunjukkan bahwa sebagian besar partai di Indonesia masih mengandalkan pendekatan top-down, sehingga aspirasi dari basis akar rumput sering kali tidak sampai ke ruang keputusan.
Lebih jauh lagi, kondisi ini menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap partai politik. Survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) beberapa tahun terakhir mencatat bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik hanya berkisar di angka 50%, lebih rendah dibanding lembaga negara lain seperti TNI atau KPK.
Rendahnya kepercayaan publik ini salah satunya dipicu oleh anggapan bahwa partai dikuasai segelintir elit yang hanya memperjuangkan kepentingan mereka sendiri. Selama partai masih dikuasai elit dan menutup ruang kaderisasi yang sehat, sulit mengharapkan lahirnya pemimpin bangsa yang berintegritas, kompeten, dan benar-benar berpihak kepada rakyat.
Politik Uang: Demokrasi yang Diperdagangkan
Praktik politik uang masih marak dalam setiap pemilu, meski regulasi semakin ketat. Data Bawaslu mencatat selama masa tenang Pemilu 2024 terdapat 70 pelanggaran di 18 provinsi, dengan 36 kasus politik uang yang teridentifikasi.
Bareskrim Polri melaporkan kasus tindak pidana pemilu menurun dari 849 kasus pada 2019 menjadi 322 laporan/temuan pada 2024, namun masih ada 65 kasus yang diproses hukum.
Fakta ini menunjukkan politik uang belum hilang, hanya lebih terselubung dan sulit dibuktikan secara hukum. Akibatnya, kualitas demokrasi tergerus karena pemimpin dipilih bukan berdasarkan kapasitas, melainkan daya beli suara.
Data Bawaslu mencatat selama masa tenang Pemilu 2024 terjadi 70 pelanggaran di 18 provinsi, dengan 36 kasus politik uang yang teridentifikasi.
Dari jumlah itu, sebagian kasus diproses hukum, namun banyak pula yang terhenti karena kesulitan pembuktian atau minimnya saksi yang berani bersuara.
Sementara itu, Bareskrim Polri melaporkan adanya penurunan jumlah laporan/temuan tindak pidana pemilu dari 849 kasus pada Pemilu 2019 menjadi 322 kasus pada Pemilu 2024, dengan 65 kasus yang diproses lebih lanjut.
Penurunan ini kerap dibaca positif, tetapi kenyataannya tidak serta merta mencerminkan berkurangnya praktik politik uang. Sebagian kasus justru lebih terselubung dan sulit diungkap karena dilakukan dengan cara-cara baru yang lebih rapi dan terstruktur.
Politik uang menciptakan siklus buruk dalam demokrasi. Calon yang membeli suara harus “mengembalikan modal” ketika terpilih, sering kali dengan praktik korupsi atau penyalahgunaan wewenang.
Akibatnya, kualitas kebijakan publik rendah, karena orientasi pejabat terpilih bukan melayani rakyat, melainkan mengembalikan biaya politik yang besar.
Transparency International Indonesia (TII) dalam laporan Corruption Perceptions Index (CPI) 2023 menempatkan Indonesia di skor 34/100, turun dari tahun sebelumnya, menunjukkan bahwa praktik korupsi masih tinggi dan salah satu penyebabnya adalah politik transaksional. Lebih jauh, politik uang juga merusak pendidikan politik masyarakat. Pemilih yang terbiasa menerima imbalan akan sulit menilai kualitas program atau visi-misi calon.
Krisis Kaderisasi: Partai Kehilangan Regenerasi
Kelemahan paling mendasar partai politik Indonesia adalah krisis kaderisasi. Partai tidak cukup serius menyiapkan generasi pemimpin yang kompeten, sehingga politik lebih diisi figur instan dengan popularitas atau modal besar. PKB, misalnya, menargetkan perekrutan 270.000 kader baru hingga 2025 melalui ribuan program kaderisasi nasional.
Meski ambisius, kualitas pendidikan kader dan ruang partisipasi mereka dalam keputusan politik masih terbatas. Di sisi lain, survei menunjukkan publik semakin skeptis; LSI melaporkan tingkat kepercayaan masyarakat pada partai politik hanya sekitar 50%, jauh lebih rendah dibanding lembaga lain seperti TNI atau KPK.
Krisis kaderisasi ini membuat partai sulit melahirkan pemimpin yang visioner, berintegritas, dan mampu menjawab tantangan masyarakat.
Krisis kaderisasi ini juga berdampak pada kualitas kepemimpinan nasional. Banyak anggota legislatif atau pejabat publik yang terpilih lebih karena nama besar keluarga, kekuatan modal, atau popularitas media, bukan karena rekam jejak politik atau kapasitasnya. Fenomena “politik dinasti” dan “politik artis” adalah gejala dari lemahnya kaderisasi partai.
Rendahnya kualitas kaderisasi turut memengaruhi tingkat kepercayaan publik. Survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik hanya sekitar 50%, jauh lebih rendah dibanding lembaga lain seperti TNI atau KPK.
Angka ini memperlihatkan bahwa masyarakat menilai partai gagal menjalankan fungsi utamanya, yaitu sebagai wahana pendidikan politik dan regenerasi kepemimpinan. Dalam jangka panjang, krisis kaderisasi mengancam keberlanjutan demokrasi Indonesia.
Jalan Reformasi: Harapan yang Masih Terbuka
Meski potret partai politik di Indonesia tampak buram akibat dominasi oligarki, maraknya politik uang, dan lemahnya kaderisasi, bukan berarti jalan perbaikan telah tertutup. Reformasi internal partai adalah kebutuhan mendesak untuk mengembalikan marwah partai sebagai pilar demokrasi.
Pertama, transparansi keuangan harus ditegakkan. Politik uang hanya bisa diputus jika pendanaan partai bersumber jelas, akuntabel, dan terbuka bagi publik. Model public funding yang diawasi ketat bisa menjadi alternatif, agar partai tidak terlalu bergantung pada donasi elit atau sponsor yang seringkali mengikat kepentingan politik.
Kedua, demokratisasi internal harus diperkuat. Seleksi calon legislatif maupun calon kepala daerah perlu dilakukan melalui mekanisme terbuka dan partisipatif, bukan semata keputusan elit. Partisipasi kader di tingkat bawah dan publik luas perlu diperbesar untuk memastikan bahwa yang diusung benar-benar representatif dan memiliki kapasitas.
Partai politik harus serius menjadikan pendidikan politik sebagai investasi jangka panjang.
Kurikulum kaderisasi seharusnya tidak berhenti pada indoktrinasi loyalitas, melainkan membangun kompetensi manajerial, etika politik, serta kepekaan terhadap persoalan rakyat. Dengan begitu, partai tidak hanya menghasilkan kader loyal, tetapi juga pemimpin berintegritas.
Langkah-langkah strategis ini membutuhkan komitmen kuat, bukan hanya dari partai politik, tetapi juga dari negara dan masyarakat sipil. Negara perlu memperkuat regulasi dan pengawasan, sementara masyarakat sipil harus aktif mengawal serta memberi tekanan agar partai benar-benar berubah. Potret buram partai politik kita memang nyata, tetapi harapan reformasi tetap ada. (*)
Ditulis oleh Lidya Nurjannah, Mahasiswi Unpam