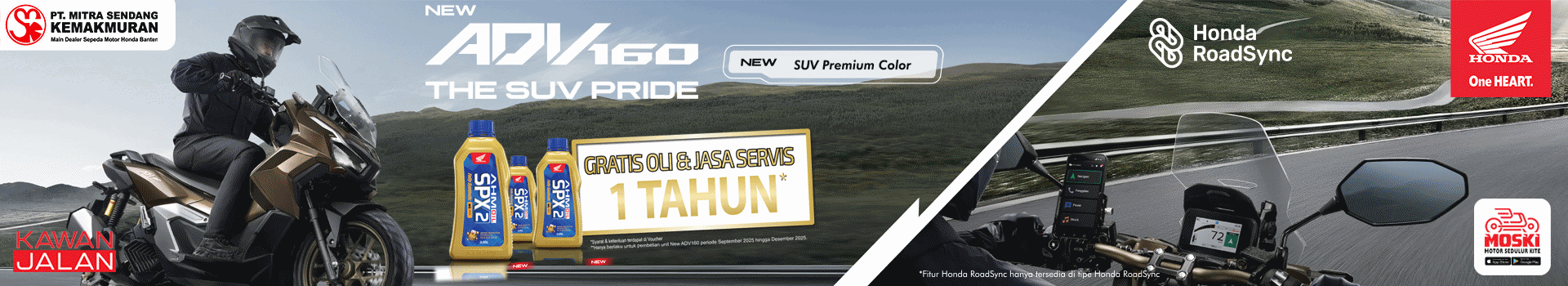Konstitusionalisme dan Negara Hukum Modern: Merefleksikan Pengalaman Indonesia

ZETIZENS.ID – Konstitusionalisme lahir sebagai reaksi atas kekuasaan absolut yang sering kali menindas rakyat. Ia menegaskan bahwa konstitusi bukan sekadar teks hukum, melainkan kontrak sosial-politik yang mengikat baik pemerintah maupun warga negara.
Dalam pandangan modern, konstitusi berfungsi membatasi kekuasaan, menciptakan mekanisme checks and balances, serta menjamin hak asasi manusia. Tanpa adanya prinsip konstitusionalisme, kekuasaan akan cenderung digunakan secara sewenang-wenang, dan rakyat kehilangan ruang perlindungan hukum.
Konsep negara hukum modern berkembang dari tradisi rule of law dan rechtsstaat. Negara hukum modern ditandai oleh beberapa prinsip: pertama, supremasi hukum, di mana setiap kebijakan pemerintah harus berdasarkan hukum; kedua, kesetaraan di depan hukum, yang menjamin tidak ada warga negara yang diperlakukan diskriminatif; ketiga, jaminan hak asasi manusia yang diakui secara konstitusional; keempat, peradilan yang bebas dari intervensi politik; dan kelima, praktik demokrasi yang memungkinkan rakyat berpartisipasi dalam penyusunan hukum.
Dalam konteks Indonesia, perjalanan konstitusionalisme dan negara hukum modern memiliki warna tersendiri.
Pada masa Orde Lama dan Orde Baru, konstitusi kerap diperlakukan sebagai alat legitimasi kekuasaan, bukan sebagai pembatas kekuasaan.
Presiden memegang kekuasaan yang dominan, bahkan superior, sehingga prinsip konstitusionalisme tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Reformasi 1998 menjadi titik balik, ketika UUD 1945 mengalami empat kali amandemen yang melahirkan pembatasan masa jabatan presiden, penguatan peran DPR, pembentukan DPD, lahirnya Mahkamah Konstitusi, dan jaminan hak asasi manusia yang lebih komprehensif.
Secara normatif, ini merupakan langkah maju dalam mewujudkan negara hukum modern. Namun, tantangan masih sangat nyata. Praktik penyelenggaraan negara memperlihatkan bahwa supremasi konstitusi sering kali dihadapkan pada kepentingan politik jangka pendek.
Fenomena korupsi sistemik, lemahnya independensi lembaga peradilan, serta kontroversi legislasi seperti UU KPK atau UU Cipta Kerja menunjukkan bahwa implementasi konstitusionalisme di Indonesia masih belum konsisten.
Meski teks konstitusi sudah ideal, budaya politik dan integritas aparat penegak hukum masih jauh dari harapan.
Dalam pandangan saya, Indonesia saat ini berada dalam proses transisi panjang menuju negara hukum modern yang sesungguhnya. Konstitusi kita sudah cukup progresif, bahkan sejalan dengan prinsip konstitusionalisme modern, tetapi realitas sosial-politik sering kali menghambat pencapaian ideal tersebut.
Konstitusionalisme tidak akan berarti apa-apa jika hanya berhenti pada level dokumen, sementara praktiknya masih mengulang pola kekuasaan yang dominan.
Negara hukum modern menuntut lebih dari sekadar teks; ia membutuhkan kesadaran kolektif bahwa hukum harus ditempatkan di atas kepentingan politik.
Jika dilihat lebih jauh, persoalan terbesar Indonesia terletak pada lemahnya integritas para penyelenggara negara.
Peradilan sering dianggap bisa dipengaruhi, partisipasi rakyat dalam legislasi masih minim, dan hukum kerap digunakan sebagai instrumen politik, bukan sebagai penjaga keadilan.
Hal ini menimbulkan paradoks: kita memiliki konstitusi yang demokratis, tetapi praktik politik masih berorientasi pada kepentingan elit.
Merefleksikan pengalaman ini, jelas bahwa tugas besar Indonesia ke depan adalah memperkuat independensi lembaga peradilan, memastikan proses legislasi lebih partisipatif, serta membangun budaya hukum yang kuat di masyarakat.
Supremasi hukum harus ditopang oleh integritas moral dan kesadaran publik, agar negara hukum tidak hanya menjadi jargon.
Konstitusionalisme akan hidup ketika warga negara dan pemerintah sama-sama konsisten menjadikan hukum sebagai rujukan utama dalam setiap tindakan. (*)
Ditulis oleh Muhammad Aril Afis, mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Semester 3, Universitas Pamulang Serang