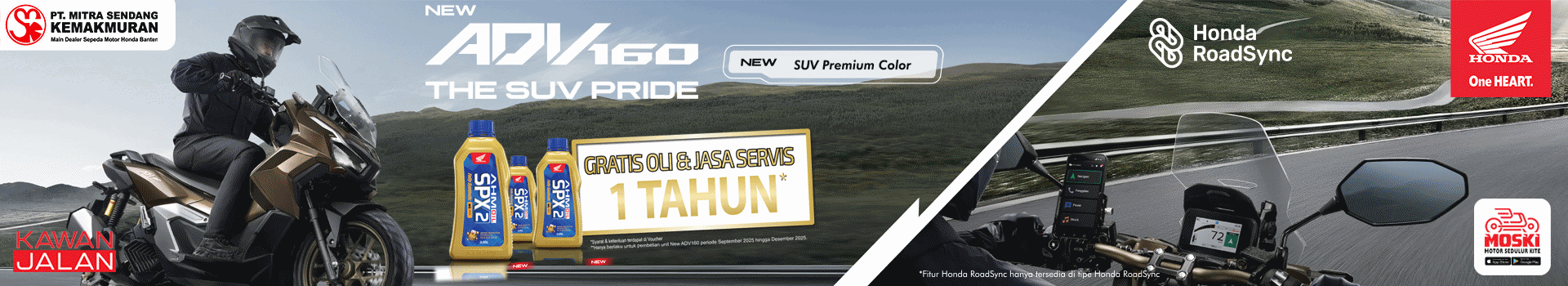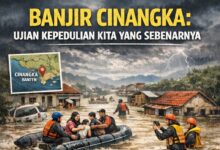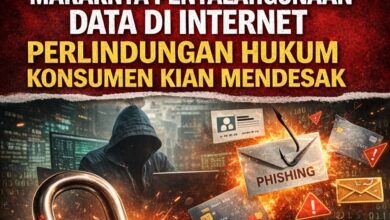Demokrasi Indonesia dan Refleksi Filsafat Klasik
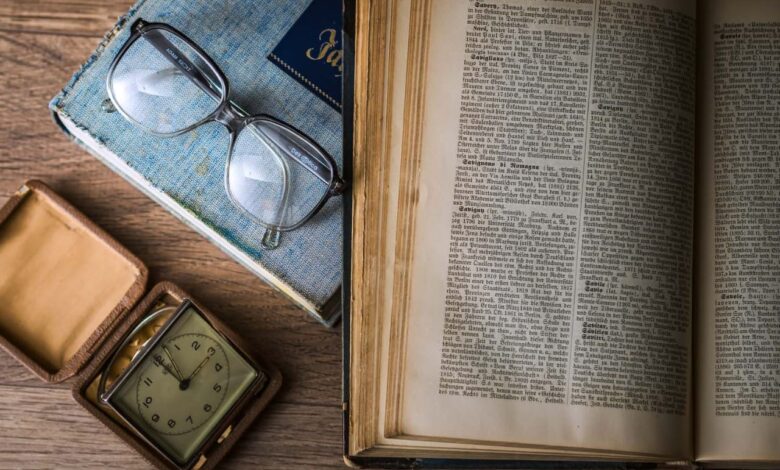
ZETIZENS.ID – Indonesia sering dielu-elukan sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, berada di urutan ketiga setelah India dan Amerika Serikat. Sistem pemilu langsung, kebebasan berpendapat, hingga keberagaman partai politik sering ditampilkan sebagai etalase keberhasilan kita. Namun, di balik layar, kondisi demokrasi Indonesia tidak selalu sehat.
Ada politik uang, dominasi oligarki, polarisasi identitas, sampai lemahnya pendidikan politik masyarakat.
Demokrasi yang seharusnya menjadi sarana rakyat untuk menentukan arah bangsa, kadang terasa lebih seperti panggung elite untuk mempertahankan kekuasaan.
Untuk memahami situasi ini, kita bisa belajar dari pemikiran filsuf klasik. Jauh sebelum Indonesia berdiri, tokoh seperti Plato, Aristoteles, dan Socrates sudah memperdebatkan soal kelebihan dan kelemahan demokrasi. Bahkan pemikir modern seperti Hobbes dan Machiavelli menambah perspektif lain.
Melihat demokrasi Indonesia lewat kacamata mereka bisa memberi gambaran lebih jelas tentang apa yang sedang terjadi dan ke mana arah yang harus kita ambil.
Masalah Demokrasi Indonesia Hari Ini
Oligarki politik dan Ekonomi
Meski secara prosedural demokrasi berjalan, substansinya sering dikendalikan oleh sekelompok kecil elite. Partai politik lebih banyak berfungsi sebagai kendaraan keluarga atau kelompok tertentu.
Mereka yang bisa maju dalam pemilu umumnya orang yang punya modal finansial besar. Akibatnya, demokrasi kehilangan esensi sebagai “pemerintahan rakyat,” dan lebih mirip arena kompetisi antar-elite kaya.
Politik Uang
Praktik transaksional masih marak dalam pemilu kita. Rakyat sering diposisikan sebagai objek yang bisa dibeli dengan sembako, amplop, atau janji kosong. Logika deliberasi dan pertimbangan rasional hilang, digantikan oleh kebutuhan sesaat. Dampaknya, kualitas pemimpin yang terpilih pun tidak selalu sebanding dengan harapan rakyat.
Polarisasi Identitas
Isu agama, suku, dan ideologi kerap digunakan sebagai senjata politik. Kampanye tidak lagi fokus pada program, melainkan membangkitkan emosi berbasis identitas. Polarisasi ini jelas berbahaya, karena bisa merusak persatuan bangsa.
Lemahnya Pendidikan Politik
Demokrasi yang sehat menuntut warga negara yang kritis. Sayangnya, literasi politik kita masih rendah. Banyak masyarakat lebih mudah percaya hoaks di media sosial dibandingkan data yang valid. Akibatnya, opini publik mudah dimanipulasi.
Plato: Demokrasi Sebagai Jalan Menuju Kekacauan
Dalam Republik, Plato menilai demokrasi sebagai sistem yang rentan jatuh ke tirani. Demokrasi, menurutnya, lahir dari keinginan rakyat akan kebebasan mutlak. Namun kebebasan tanpa batas membuat orang kehilangan arah, sehingga membuka ruang bagi hadirnya pemimpin otoriter.
Jika kita kaitkan dengan Indonesia, situasinya tidak jauh berbeda. Kita memang punya kebebasan berpendapat, tetapi tanpa dasar pendidikan politik yang matang, kebebasan itu sering disalahgunakan.
Media sosial penuh ujaran kebencian dan politik identitas. Dalam kondisi seperti ini, masyarakat mudah merasa lelah dengan kebisingan demokrasi, lalu berharap hadirnya figur kuat yang bisa “menertibkan.” Inilah yang dikhawatirkan Plato: demokrasi yang akhirnya melahirkan tirani.
Aristoteles: Jalan Tengah dan Kepentingan Umum
Berbeda dari Plato, Aristoteles tidak menolak demokrasi sepenuhnya. Dalam Politik, ia berpendapat bahwa demokrasi bisa berjalan baik asalkan diarahkan untuk kepentingan umum, bukan hanya kepentingan kelompok tertentu. Ia memperkenalkan konsep polity, yaitu bentuk pemerintahan campuran antara demokrasi dan oligarki.
Dalam konteks Indonesia, gagasan Aristoteles sangat relevan. Kita membutuhkan sistem yang menjaga partisipasi rakyat, tetapi juga punya institusi yang kuat untuk menahan dominasi oligarki.
Demokrasi tidak boleh kebablasan menjadi sekadar ajang kebebasan, tapi juga tidak bisa hanya jadi alat elite. Kuncinya ada pada keseimbangan: membatasi kekuatan modal politik, memperkuat hukum, serta mendorong transparansi.
Socrates: Pentingnya Dialog dan Kesadaran Kritis
Socrates terkenal dengan metode elenchus, yaitu tanya-jawab kritis untuk menggugah kesadaran orang. Ia percaya bahwa kebijaksanaan lahir dari dialog dan refleksi, bukan dari menerima sesuatu secara pasif.
Sayangnya, kondisi masyarakat Indonesia sering berlawanan. Banyak orang memilih kandidat hanya karena ikut arus, karena popularitas, atau karena iming-iming materi.
Jika Socrates hidup di sini, mungkin ia akan turun ke alun-alun, bertanya pada orang-orang: “Kenapa kamu pilih calon itu? Apakah kamu betul-betul tahu siapa dia?”
Ironisnya, Socrates sendiri dihukum mati karena sikap kritisnya dianggap mengganggu. Itu menjadi pengingat bahwa demokrasi pun bisa menyingkirkan suara kritis, padahal suara itulah yang menjaga demokrasi tetap sehat.
Hobbes dan Machiavelli: Bayangan Realitas
Thomas Hobbes menekankan pentingnya otoritas kuat untuk mencegah manusia jatuh ke dalam kondisi “perang semua melawan semua.”
Dalam situasi demokrasi Indonesia yang penuh polarisasi, pandangan ini relevan. Tanpa aturan hukum yang kuat, perbedaan politik bisa berkembang menjadi konflik sosial yang berbahaya.
Sementara itu, Machiavelli melihat politik secara lebih sinis. Baginya, politik bukan soal moral, melainkan soal bagaimana kekuasaan dipertahankan. Jika jujur, demokrasi kita sering lebih dekat dengan praktik Machiavelli. Janji kampanye, manipulasi citra, hingga pengkhianatan politik sudah dianggap hal biasa. Politik lebih sering soal strategi, bukan kepentingan rakyat.
Demokrasi Indonesia: Antara Idealisme dan Realitas
Jika dirangkum dari refleksi para filsuf klasik, kondisi demokrasi Indonesia bisa dipahami begini:
Plato benar ketika mengingatkan bahaya kebebasan tanpa kendali. Demokrasi kita kadang liar, penuh provokasi, dan mudah disalahgunakan.
Aristoteles menawarkan jalan keluar: demokrasi harus dijalankan demi kepentingan umum dengan keseimbangan antara rakyat dan elite.
Socrates mengingatkan bahwa rakyat harus kritis dan mau berdialog, bukan sekadar pasif.
Hobbes memperingatkan bahaya anarki jika institusi tidak cukup kuat.
Machiavelli menunjukkan sisi realistis bahwa politik sering hanya soal perebutan kekuasaan.
Dari sini terlihat, demokrasi Indonesia tidak cukup diukur hanya dari keberadaan pemilu.
Demokrasi harus diukur dari sejauh mana rakyat benar-benar bisa memengaruhi kebijakan publik. Kita butuh pendidikan politik yang serius, lembaga hukum yang tegas, serta masyarakat yang mau berpikir kritis.
Sejak reformasi 1998, Indonesia telah memilih jalan demokrasi. Itu adalah pencapaian besar yang patut dipertahankan. Namun, demokrasi bukan tujuan akhir, melainkan proses yang selalu diuji.
Pemikiran filsuf klasik memberi kita cermin: demokrasi bisa jatuh ke tirani jika kebebasan tidak terkendali, bisa mandek dalam oligarki jika elite terus berkuasa, atau bisa tumbuh sehat jika diarahkan untuk kepentingan umum.
Masa depan demokrasi Indonesia bergantung pada kita. Jika rakyat tetap pasif, gampang dimanipulasi, dan hanya menunggu janji, maka demokrasi akan terus menjadi ritual lima tahunan tanpa substansi. Tetapi jika rakyat berani berpikir kritis, aktif dalam dialog, dan menuntut keadilan, demokrasi masih punya harapan untuk tumbuh lebih matang.
Dengan kata lain, demokrasi Indonesia adalah panggung besar. Pertanyaannya, apakah rakyat hanya mau jadi penonton, atau ikut menulis naskah dan mengarahkan jalan ceritanya.(*)
Ditulis oleh Aisyah Balqisi Khairotunisa, mahasiswa Ilmu Pemerintahan Unpam PSDKU Serang