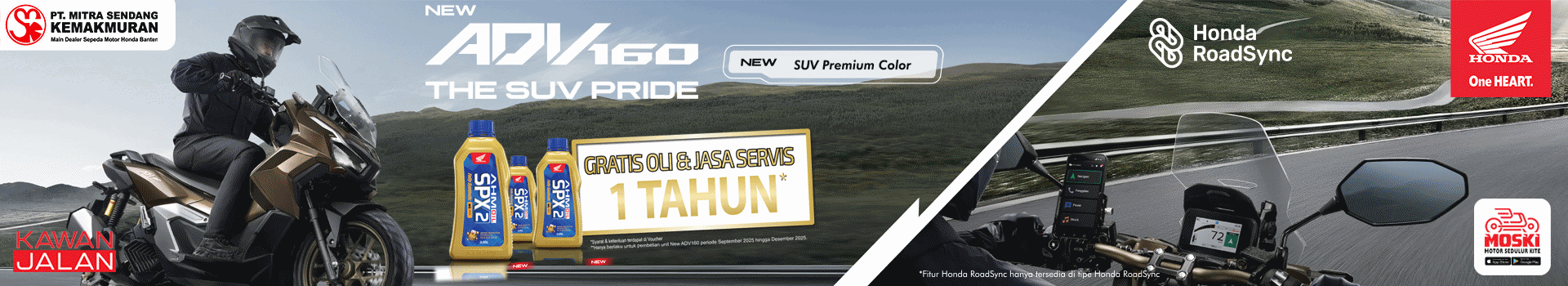Kontrak Sosial Indonesia: Janji yang Tak Pernah Tuntas

ZETIZENS.ID – Kontrak sosial sering dibayangkan sebagai fondasi lahirnya negara: rakyat menyerahkan sebagian kebebasannya dengan harapan negara melindungi, menyejahterakan, dan mendengar mereka.
Di atas kertas, konsep ini tampak rapi. Tapi ketika kita menengok Indonesia hari ini, muncul rasa ganjil: benarkah kontrak itu pernah disepakati bersama, atau hanya ditafsirkan oleh segelintir elit?
Reformasi 1998 sering dianggap sebagai upaya memperbaiki kontrak sosial ala Orde Baru. Namun dua dekade berjalan, aroma negosiasi sepihak masih kentara. Wajah kontraknya baru, tapi tanda tangannya tetap didominasi mereka yang punya kuasa dan modal.
Saat Kontrak Dikuasai Segelintir
Revisi UU KPK, Omnibus Law Cipta Kerja, dan sederet kebijakan lain memperlihatkan bahwa keputusan negara sering lahir tanpa melibatkan publik secara bermakna. Partisipasi warga ada, tapi hanya sebatas formalitas: dengar pendapat terbatas, konsultasi daring, lalu kebijakan diputuskan tanpa mengubah substansi.
Di titik ini, pernyataan Satjipto Rahardjo terasa relevan: hukum seharusnya melindungi manusia, bukan menjadi alat legal dari kepentingan kuat. Kalau kontrak sosial hanya mengunci warga dalam kewajiban tanpa perlindungan, itu bukan kontrak melainkan penyerahan sepihak.
Demokrasi Kita: Suara Ada, Kuasa Tidak
Pemilu langsung memberi ruang memilih, tapi akses mencalonkan diri tetap mahal. Dinasti politik dan oligarki ekonomi makin kuat mencengkeram. Di balik jargon “daulat rakyat”, keputusan penting sering diambil tanpa melibatkan mereka yang terdampak.
Mohammad Hatta pernah mengingatkan: kemerdekaan tak berarti apa-apa bila rakyat hanya jadi penonton. Tapi hari ini, kritik publik bisa dijawab dengan pasal karet UU ITE, stigmatisasi, atau pembungkaman halus. Negara menuntut loyalitas, tapi lambat mendengar keresahan.
Warga Mulai Menagih
Meski kekuasaan sering menutup telinga, masyarakat tidak sepenuhnya diam. Petani Kendeng, masyarakat adat Kalimantan dan Papua, jaringan advokasi lingkungan, buruh, mahasiswa, hingga jurnalis investigatif berulang kali menginterupsi narasi tunggal negara.
Yudi Katif mengingatkan, Pancasila seharusnya jadi ruh kontrak sosial Indonesia: keadilan, kebersamaan, dan musyawarah. Kalau negara makin jauh dari nilai itu, legitimasi moralnya ikut runtuh.
Kontrak Sosial yang Membumi
Kalau kontrak sosial ingin hidup dan bukan hanya slogan, ada beberapa syarat minimal:
• Warga dilibatkan sejak awal, bukan setelah keputusan jadi.
• Keamanan dan kesejahteraan bukan hanya bicara pertumbuhan, tetapi perlindungan atas tanah, suara, tubuh, dan martabat.
• Kekuasaan harus akuntabel, bukan kebal kritik dan hukum.
Kontrak Itu Harus Ditagih, Bukan Diimani
Kontrak sosial tidak mati sendirinya. Ia mati jika warga berhenti merawat dan menagihnya. Indonesia kini berada di persimpangan: menjadikan kontrak sosial sekadar retorika negara, atau menghidupkannya kembali sebagai kesepakatan yang nyata.
Pertanyaan paling mendesak hari ini mungkin bukan lagi “apa isi kontraknya?”, tapi: apakah rakyat sungguh dianggap sebagai pihak yang ikut menyepakati, atau hanya nama yang di catut untuk membenarkan keputusan kekuasaan? (*)
Ditulis oleh Rachmita Widiya Putri, mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik semester tiga di Universitas Pamulang.