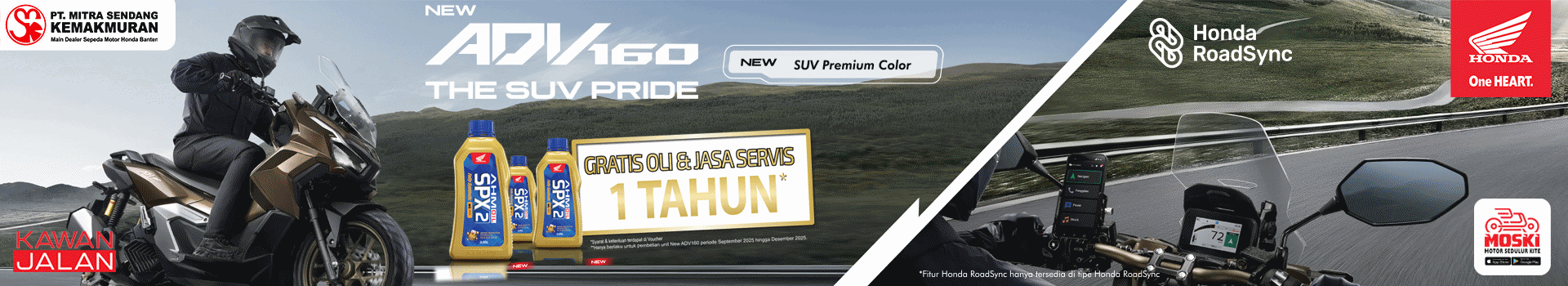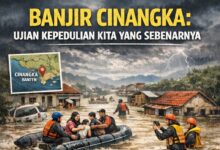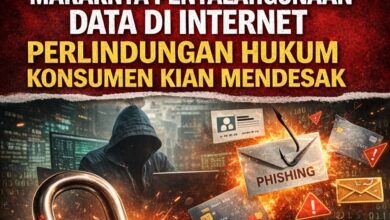Demokrasi Indonesia dalam Renungan Filsafat Klasik: Dari Rutinitas Menuju Makna
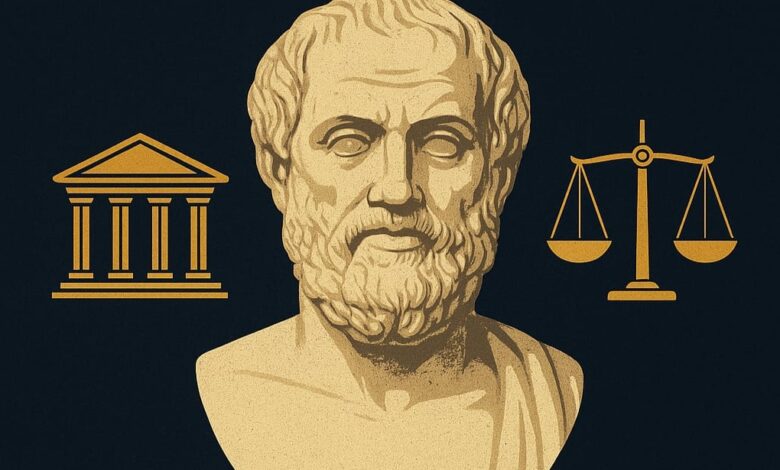
ZETIZENS.ID – Demokrasi sering dipandang sebagai salah satu capaian terbesar dalam sejarah peradaban politik modern. Sejak Reformasi 1998, Indonesia menempatkan demokrasi sebagai fondasi kehidupan bernegara. Meski demikian, setelah lebih dari dua puluh tahun, banyak kritik muncul.
Proses demokratis seperti pemilu berjalan secara rutin, partai politik tetap hidup, dan kebebasan berpendapat relatif terjaga. Namun, makna terdalam dari demokrasi yakni keadilan, perlindungan hak, serta kesejahteraan rakyat yang elum dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat.
Tulisan BEM Kema Unpad (2024) menyoroti kelemahan demokrasi Indonesia dengan menekankan bahwa praktiknya lebih banyak menjadi instrumen elit ketimbang cerminan kedaulatan rakyat.
Di sisi lain, Zetizens.id mengajak pembaca kembali merenungkan gagasan para filsuf klasik Plato, Aristoteles, hingga Locke untuk mengingatkan bahwa demokrasi bukan semata prosedur memilih pemimpin, melainkan bagaimana kekuasaan dipakai untuk kebaikan publik.
Dari kedua perspektif ini, tampak bahwa problem inti demokrasi kita adalah jarak yang lebar antara ritual prosedural dan substansi nilai yang seharusnya hadir.
Plato adalah salah satu pemikir yang paling skeptis terhadap demokrasi. Ia menganggap sistem ini berpotensi melahirkan kekacauan karena rakyat mudah dipengaruhi janji-janji manis dan retorika, sehingga akhirnya mengangkat pemimpin yang populer alih-alih yang bijaksana.
Bagi Plato, pemimpin ideal adalah philosopher-king seorang penguasa yang berlandaskan kebijaksanaan. Kondisi Indonesia hari ini tampaknya menguatkan pandangannya: politik pencitraan dan popularitas kerap lebih menentukan dibanding integritas dan kapasitas intelektual seorang calon pemimpin.
Aristoteles menawarkan sudut pandang yang lebih moderat. Ia menilai demokrasi dapat diterima sejauh dilaksanakan demi kepentingan bersama.
Menurutnya, bentuk pemerintahan yang baik adalah politeia, yaitu ketika banyak orang berpartisipasi, tetapi tetap diarahkan untuk kebaikan kolektif.
Sayangnya, praktik demokrasi di Indonesia lebih sering menunjukkan dominasi oligarki terselubung. Kebijakan penting kerap diputuskan oleh segelintir elit, sementara kepentingan rakyat banyak tidak terakomodasi.
John Locke, melalui teori kontrak sosial, menegaskan bahwa pemerintahan sah hanya jika mampu menjamin hak dasar warganya: hak hidup, kebebasan, dan kepemilikan.
Ketika negara gagal melindungi hak-hak ini, maka legitimasi pemerintahan runtuh. Situasi Indonesia, yang masih diwarnai korupsi sistemik, lemahnya penegakan hukum, dan ketimpangan ekonomi, menunjukkan kontrak sosial belum berjalan sebagaimana mestinya.
Dari ketiga filsuf tersebut, jelas bahwa demokrasi Indonesia masih menghadapi masalah serius: terlalu menekankan prosedur formal, tetapi abai pada substansi.
Ada beberapa persoalan pokok yang tampak jelas dalam realitas demokrasi kita. Pertama, praktik politik uang masih mendominasi. Pemilu sering berubah menjadi ajang transaksi, bukan kontestasi gagasan, sehingga kepentingan publik kalah oleh kekuatan modal.
Kedua, politik identitas masih menjadi senjata efektif bagi sebagian elit. Demokrasi yang seharusnya menyatukan justru terjebak dalam polarisasi berbasis agama, etnis, atau kelompok.
Ketiga, institusi demokrasi belum sepenuhnya kokoh. Mekanisme kontrol antarlembaga tidak berjalan optimal karena banyak lembaga negara mudah dipengaruhi kepentingan politik.
Keempat, ruang publik yang semrawut. Media sosial, alih-alih menjadi arena diskusi sehat, justru sarat hoaks, ujaran kebencian, dan polarisasi dangkal. Kondisi ini justru mengikis kualitas deliberasi publik yang seharusnya menopang demokrasi.
Keempat masalah ini menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia baru hadir dalam bentuk luar, tetapi masih kosong dalam makna substantifnya.
Bagi saya, demokrasi Indonesia tidak boleh berhenti pada ritual prosedural semata. Demokrasi yang hanya hadir setiap lima tahun dalam bentuk pemilu tanpa menghadirkan kebijakan adil dan berpihak pada rakyat hanyalah slogan kosong. Jika dibiarkan, sistem ini akan semakin terkonsentrasi di tangan oligarki dan akhirnya kehilangan legitimasi di mata masyarakat.
Saya percaya, demokrasi Indonesia baru akan bermakna jika kita berani menggeser orientasi dari sekadar prosedur menuju substansi. Ini membutuhkan masyarakat yang matang secara politik, yang tidak mudah dibeli dengan uang atau terjebak dalam retorika populis.
Selain itu, demokrasi kita hanya akan kuat bila institusinya independen dan tegas menegakkan aturan, bukan alat bagi elit yang berkuasa. Ruang publik juga harus dibersihkan dari praktik yang merusak diskursus, sehingga bisa menjadi arena dialog yang rasional.
Dan yang terpenting, demokrasi harus diarahkan pada tujuannya yang hakiki: menghadirkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat.
Dalam konteks ini, ajaran para filsuf klasik tetap relevan. Plato memperingatkan agar rakyat berhati-hati memilih pemimpin bukan karena popularitas, tetapi karena kebijaksanaan. Aristoteles mengingatkan bahwa demokrasi sejati adalah yang berpihak pada kepentingan umum.
Locke menekankan pentingnya menghormati kontrak sosial dengan rakyat. Ketiganya memberi fondasi moral dan intelektual agar demokrasi Indonesia bisa tumbuh melampaui sekadar prosedur dan benar-benar mengabdi pada rakyat.
Demokrasi Indonesia hari ini bisa diibaratkan sebagai pohon rindang yang terlihat kokoh dari luar, tetapi akarnya lapuk. Ia tampak hidup, tetapi rapuh di dalam. Filsafat klasik memberi peringatan penting bahwa demokrasi bukan hanya soal pemilu, melainkan menyangkut kebijaksanaan, keadilan, dan penghormatan terhadap hak-hak rakyat.
Pandangan saya yaitu demokrasi Indonesia harus bertransformasi dari sekadar rutinitas menuju esensi. Tanpa itu, demokrasi akan terus menjadi slogan hampa yang jauh dari cita-cita reformasi. Namun, jika refleksi Plato, Aristoteles, dan Locke benar-benar dijadikan pedoman dan masyarakat mampu meningkatkan kesadaran politiknya, maka demokrasi Indonesia masih memiliki harapan besar untuk tumbuh menjadi sistem politik yang otentik yaitu lahir dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan ditujukan untuk rakyat. (*)
Ditulis oleh Herlinda, Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Pamulang Semester 3