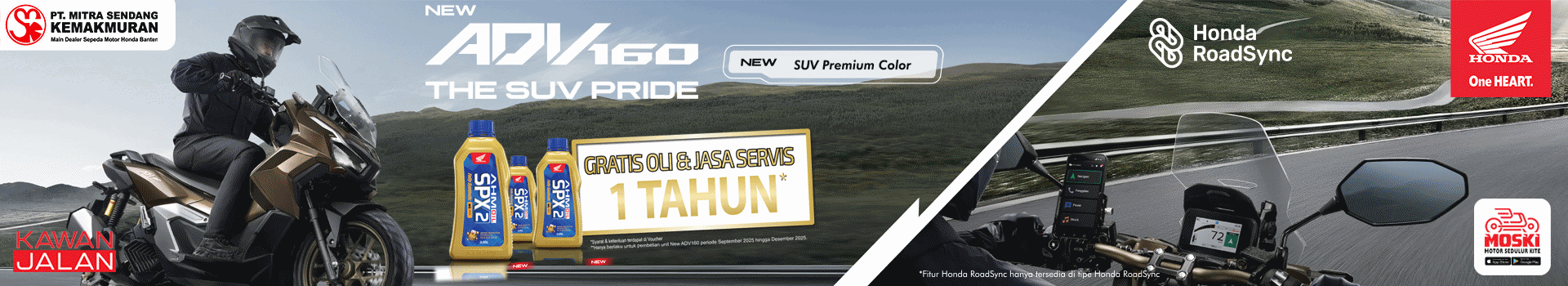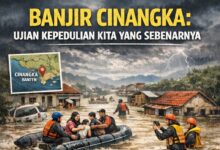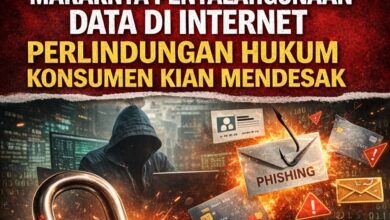Demokrasi Indonesia di Persimpangan: Refleksi Klasik untuk Zaman Modern
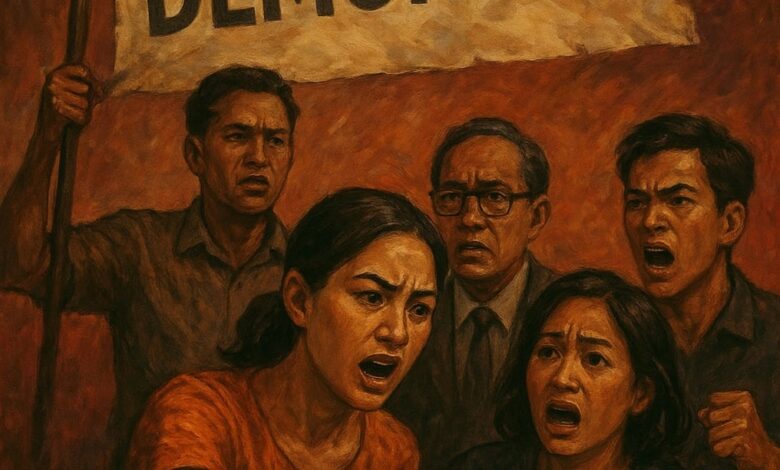
ZETIZENS.ID – Demokrasi Indonesia selalu dipuji sebagai salah satu yang paling besar di dunia. Dengan lebih dari 200 juta pemilih, pemilu kita adalah pesta rakyat raksasa yang melibatkan energi, emosi, dan biaya yang tidak sedikit.
Tapi di balik semua gegap gempita itu, banyak dari kita mulai bertanya-tanya: apakah demokrasi kita benar-benar membawa kita ke arah yang lebih baik, atau malah sedang tersesat?
Pertanyaan ini bukan cuma keluhan generasi muda yang skeptis, tapi kegelisahan nyata melihat praktik politik uang, polarisasi yang makin tajam, dan elite yang itu-itu saja memegang kendali.
Kalau kita mundur sejenak, filsuf-filsuf klasik sebenarnya sudah lama mengingatkan kita tentang sisi gelap demokrasi. Plato, dalam karyanya Republic, menggambarkan demokrasi sebagai sistem yang penuh kebebasan, di mana setiap orang bisa melakukan apa yang mereka mau.
Kedengarannya keren, tapi Plato khawatir kebebasan tanpa kendali akan memunculkan kekacauan, lalu membuka jalan bagi tiran. Ini ironisnya mirip dengan kondisi kita sekarang.
Banyak orang merasa punya hak bersuara, tapi mudah sekali diprovokasi isu dangkal seperti politik identitas.
Parahnya, suara rakyat bisa “dibeli” dengan amplop atau janji populis. Ini bukan kebebasan yang Plato bayangkan, tapi kebebasan yang dipelintir.
Aristoteles menawarkan sudut pandang yang sedikit lebih optimis. Dia percaya demokrasi bisa baik kalau dijalankan dalam bentuk polity, yaitu pemerintahan yang mengutamakan kepentingan bersama, bukan kepentingan kelompok sempit.
Menurut Aristoteles, masyarakat yang punya kelas menengah kuat biasanya bisa menjaga keseimbangan kekuasaan sehingga demokrasi tidak jatuh ke tangan segelintir orang kaya atau massa yang gampang diprovokasi.
Nah, masalahnya di Indonesia, kelas menengah kita justru sering apatis atau sibuk dengan urusan pribadi. Akibatnya, ruang politik dikuasai oleh elite yang punya uang dan pengaruh, sementara mayoritas rakyat cuma jadi penonton.
Fenomena demagogi yang diperingatkan Aristoteles juga terasa kental di sini. Demagog adalah pemimpin yang mengandalkan retorika emosional untuk meraih kekuasaan, bukan gagasan rasional.
Kita sering melihat politisi yang lebih sibuk memainkan emosi—entah lewat sentimen agama, nasionalisme berlebihan, atau gimmick media sosial—daripada menawarkan solusi konkret. Akhirnya, demokrasi kita jadi seperti drama tanpa akhir, penuh konflik tapi minim hasil nyata untuk rakyat.
Kalau kita menoleh pada Cicero, filsuf sekaligus negarawan Romawi, ada satu hal yang ia tekankan habis-habisan: supremasi hukum atau rule of law.
Bagi Cicero, hukum harus berdiri di atas kepentingan siapa pun, bahkan penguasa. Tanpa hukum yang adil, negara akan jatuh ke dalam tirani atau anarki.
Di Indonesia, kita sering mendengar istilah “hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas.” Korupsi yang sudah jadi penyakit kronis, kasus hukum yang bisa “diatur”, dan aparat yang tidak selalu netral, membuat demokrasi kita terasa pincang.
Kalau hukum hanya jadi alat untuk mengamankan kekuasaan, bagaimana rakyat bisa percaya bahwa demokrasi bekerja untuk mereka?
Refleksi dari Plato, Aristoteles, dan Cicero ini seharusnya jadi alarm bagi kita. Demokrasi bukan cuma soal memilih pemimpin lima tahun sekali, tapi soal membangun budaya politik yang sehat.
Kita perlu memperkuat pendidikan politik agar rakyat nggak gampang termakan hoaks atau rayuan populis. Kita juga harus mendorong transparansi, supaya uang dan kekuasaan tidak bermain di belakang layar.
Dan yang paling penting, kita butuh penegakan hukum yang benar-benar adil, sehingga siapa pun yang salah harus bertanggung jawab, tanpa pandang bulu.
Masalahnya, semua itu nggak bisa selesai hanya dengan mengandalkan elite politik. Rakyat harus ikut ambil bagian. Demokrasi yang sehat butuh partisipasi aktif, bukan Cuma pas hari pemilu.
Kita bisa mulai dari hal kecil: ikut diskusi publik, kritis terhadap kebijakan, dan berani bersuara kalau ada ketidakadilan. Di era digital, suara kita bahkan bisa lebih didengar daripada dulu, tinggal bagaimana kita memanfaatkannya dengan bijak, bukan sekadar menyebar ujaran kebencian atau gosip politik.
Memang, membenahi demokrasi itu nggak instan. Plato sendiri sebenarnya nggak percaya demokrasi bisa bertahan lama, karena terlalu rawan disalahgunakan. Tapi kita punya kesempatan untuk membuktikan sebaliknya. Demokrasi Indonesia bisa lebih matang jika kita belajar dari kesalahan, memperbaiki sistem, dan menuntut akuntabilitas dari para pemimpin.
Jadi, apakah demokrasi Indonesia sedang gagal? Mungkin belum. Tapi kalau kita terus diam dan membiarkan semua keburukan ini berlangsung, demokrasi hanya akan jadi formalitas. Kita akan terus memilih, tapi tidak pernah benar-benar berdaulat.
Refleksi dari para filsuf klasik tadi seharusnya membuat kita sadar: demokrasi adalah proyek bersama yang harus terus dijaga, atau dia akan hilang perlahan. (*)
Ditulis oleh Ahmad Faqih Firmansyah, mahasiswa Ilmu Pemerintahan Unpam PSDKU Serang