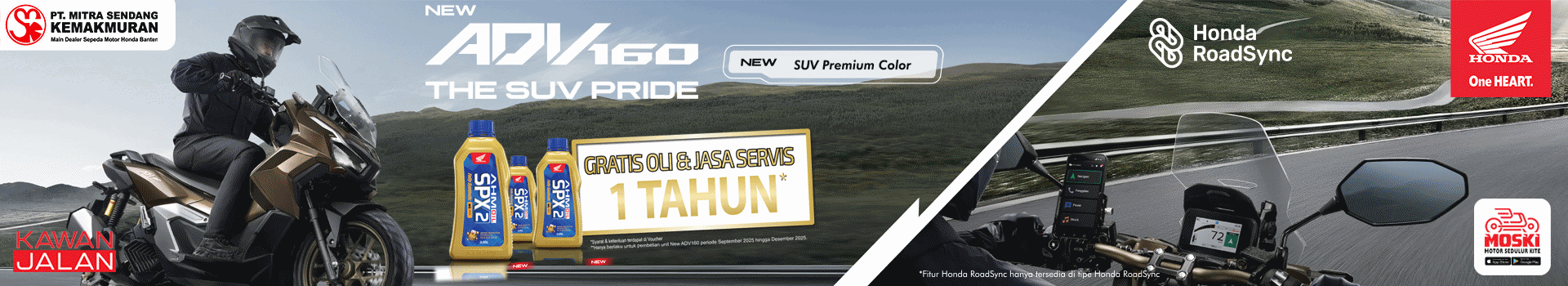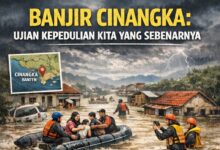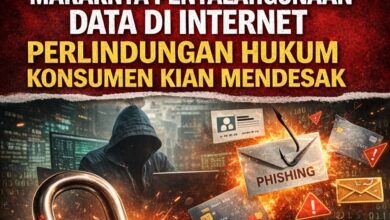Montesquieu dan Pemisahan Kekuasaan: Menguji Demokrasi Indonesia
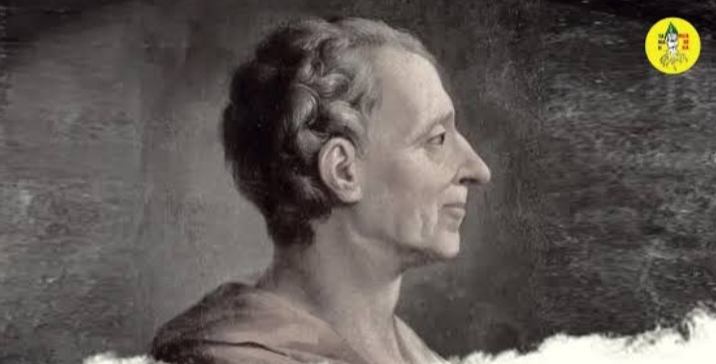
ZETIZENS.ID – Demokrasi Indonesia kerap dipuji sebagai salah satu yang terbesar di dunia. Dengan lebih dari 200 juta pemilih dan pemilu yang rutin diselenggarakan, bangsa ini sering dianggap sebagai bukti bahwa demokrasi bisa tumbuh di negara dengan keragaman luar biasa.
Namun, di balik kebanggaan itu, pertanyaan kritis selalu muncul: apakah demokrasi kita benar-benar berdiri kokoh di atas prinsip pemisahan kekuasaan, atau hanya formalitas belaka?
Pertanyaan ini bukan sekadar akademis. Ia menyentuh jantung persoalan politik kita hari ini.
Banyak orang percaya bahwa demokrasi cukup diwujudkan lewat pemilu yang bebas dan adil. Padahal, tanpa mekanisme pemisahan kekuasaan yang efektif, demokrasi bisa kehilangan rohnya.
Di sinilah gagasan klasik Montesquieu terasa penting untuk kita angkat kembali ke panggung perdebatan publik.
Montesquieu, seorang filsuf politik asal Prancis abad ke-18, memperkenalkan konsep trias politica—pemisahan kekuasaan ke dalam tiga cabang: eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Baginya, kekuasaan yang tidak dipisahkan hanya akan berakhir pada tirani. Kekuasaan, kata Montesquieu, cenderung disalahgunakan jika tidak dibatasi. Karena itu, setiap cabang kekuasaan harus memiliki fungsi kontrol terhadap cabang lainnya.
Demokrasi yang sehat, menurutnya, bukan sekadar soal siapa yang berkuasa, melainkan bagaimana kekuasaan itu dibatasi dan diawasi.
Indonesia, secara konstitusional, sudah mengadopsi prinsip ini. Presiden memegang cabang eksekutif, DPR dan DPD menjalankan legislatif, sementara MA dan MK berada di ranah yudikatif. Namun, praktik politik sehari-hari menunjukkan bahwa garis pemisah tersebut sering kabur.
Kita melihat bagaimana eksekutif dan legislatif kerap berjalan seiring dalam kepentingan politik yang sama, sementara yudikatif tidak selalu bisa berdiri independen di hadapan tekanan kekuasaan.
Contoh nyata bisa kita lihat dalam revisi Undang-Undang KPK pada 2019. DPR bersama pemerintah terlihat begitu kompak mendorong pelemahan lembaga antikorupsi.
Publik yang marah turun ke jalan, tetapi suara rakyat tidak cukup kuat untuk mengubah arah kebijakan.
Dalam kerangka Montesquieu, situasi ini memperlihatkan bahwa fungsi legislatif sebagai pengawas eksekutif telah melemah, bahkan cenderung larut dalam arus kekuasaan.
Sisi lain, cabang yudikatif juga menghadapi ujian serius. Mahkamah Konstitusi, misalnya, sempat menjadi sorotan tajam akibat kasus etik yang menjerat salah satu hakimnya.
Padahal, lembaga ini merupakan benteng terakhir rakyat dalam menjaga konstitusi. Ketika independensi MK goyah, publik tentu mempertanyakan apakah keadilan benar-benar bisa ditegakkan tanpa campur tangan politik. Montesquieu barangkali akan mengernyitkan dahi jika menyaksikan hal ini: lembaga yang seharusnya berdiri tegak justru bisa terguncang oleh kepentingan sesaat.
Jika kita tarik ke belakang, Indonesia sebenarnya pernah mengalami fase ketika pemisahan kekuasaan hampir tidak berjalan sama sekali.
Pada masa Orde Baru, eksekutif begitu dominan, legislatif hanya menjadi “stempel” kebijakan pemerintah, dan yudikatif tidak berdaya menghadapi intervensi politik.
Reformasi 1998 membuka jalan untuk memperbaiki kondisi ini, tetapi setelah lebih dari dua dekade, kita masih menyaksikan bayang-bayang lama yang kembali menghantui.
Dominasi eksekutif tetap terasa kuat, sementara peran legislatif dan yudikatif sering melemah ketika berhadapan dengan kepentingan kekuasaan.
Mengapa hal ini bisa terjadi? Salah satu jawabannya terletak pada politik koalisi. Sistem presidensial Indonesia hampir selalu menghasilkan pemerintahan yang didukung oleh mayoritas besar di parlemen.
Koalisi gemuk memang bisa menciptakan stabilitas, tetapi sekaligus berisiko melemahkan fungsi kontrol. DPR yang terlalu dekat dengan pemerintah akan kesulitan menjalankan peran sebagai pengawas. Alih-alih menyeimbangkan, mereka justru menjadi perpanjangan tangan eksekutif.
Selain itu, independensi yudikatif juga kerap diguncang oleh problem internal, mulai dari isu etik hingga integritas hakim. Mahkamah Agung masih bergelut dengan kasus korupsi di lingkungannya, sementara Mahkamah Konstitusi harus berjuang menjaga kepercayaan publik.
Semua ini memperlihatkan bahwa pemisahan kekuasaan di atas kertas tidak selalu sejalan dengan praktik di lapangan.
Jika Montesquieu bisa berbicara langsung kepada kita, ia mungkin akan mengingatkan bahwa demokrasi bukan hanya soal prosedur, tetapi juga substansi.
Pemilu yang rutin dilaksanakan tidak akan cukup jika tidak disertai mekanisme checks and balances yang kuat. Tanpa itu, demokrasi bisa berubah menjadi otoritarianisme yang berkedok demokrasi—sebuah paradoks yang sering kita lihat di banyak negara berkembang.
Namun, bukan berarti harapan sudah hilang. Justru refleksi atas pemikiran Montesquieu bisa menjadi kompas untuk memperbaiki demokrasi kita.
Ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Pertama, memperkuat lembaga legislatif agar benar-benar menjalankan fungsi pengawasan. DPR harus lebih berani bersuara kritis, meskipun berhadapan dengan pemerintah yang didukung mayoritas besar.
Kedua, membangun integritas lembaga yudikatif melalui transparansi, akuntabilitas, dan penegakan kode etik yang tegas. Ketiga, mendorong partisipasi masyarakat sipil agar tetap menjadi pengawal demokrasi di luar struktur negara.
Demokrasi Indonesia memang telah melangkah jauh sejak reformasi, tetapi jalan menuju demokrasi yang matang masih panjang.
Selama pemisahan kekuasaan belum dijaga dengan sungguh-sungguh, demokrasi kita akan terus rapuh dan mudah dipermainkan oleh elite. Montesquieu pernah berpesan bahwa kebebasan hanya bisa terjamin jika kekuasaan saling mengawasi dan membatasi. Pesan itu masih sangat relevan bagi kita hari ini.
Pada akhirnya, demokrasi Indonesia harus kita pahami bukan sekadar sebagai rutinitas politik lima tahunan, melainkan sebagai upaya terus-menerus untuk menyeimbangkan kekuasaan.
Tanpa keseimbangan itu, rakyat hanya akan menjadi penonton di panggung politik yang dikendalikan segelintir elite. Pertanyaannya sederhana namun mendalam: apakah kita ingin demokrasi yang sungguh-sungguh hidup, atau hanya demokrasi yang sekadar ada namanya? (*)
Ditulis oleh Ahmad Bilhaq, mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan Semester 3, Universitas Pamulang PSDKU serang