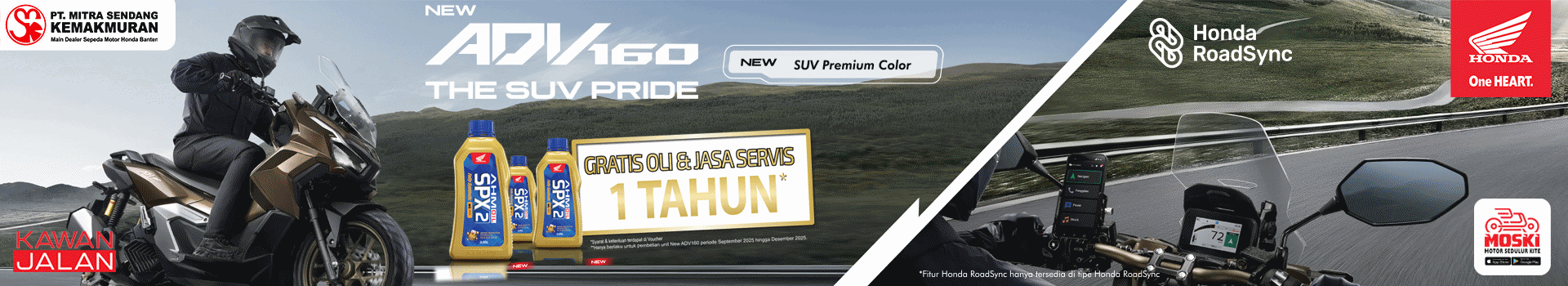Pisang Cokelat dan Kemiskinan: Hidangan Buka Puasa yang Tak Pernah Kita Pesan

ZETIZENS.ID – Menjelang buka puasa pada 15 Maret 2025, sekitar pukul 16.26 WIB, Masjid Agung Banten mulai dipenuhi jamaah.
Orang-orang duduk berkelompok, menanti adzan maghrib dengan wajah damai. Aku sendiri menikmati angin sore, ketika tiba-tiba seorang bocah laki-laki datang, membawa kotak box berisi pisang cokelat yang tampak dingin dan berminyak.
“Mbak, beli piscok, dong. Enak, lho,” katanya dengan suara penuh harapan.
Anak itu tak lebih dari 10 tahun. Bajunya lusuh, rambutnya berantakan, dan di wajahnya ada sesuatu yang mengganggu sebuah ketakutan yang sulit dijelaskan.
“Maaf ya, Dek. Aku nggak beli,” jawabku, mencoba tetap lembut.
Sekejap, ekspresinya berubah. Tatapannya tajam, menusuk seolah aku baru saja merampas sesuatu darinya.
“Mbak kan orang gede, masa nggak bisa bantu? Kalau aku nggak jualan, aku nggak bisa makan.”
Tiba-tiba, aku merasa seolah ditelanjangi oleh bocah ini. Aku hanya ingin menunggu waktu berbuka, tapi di depanku ada seorang anak kecil yang bahkan tak tahu apakah dia bisa makan hari ini atau tidak.
Aku menelan ludah, merasa bersalah meski tak melakukan apa-apa. “Beneran, Dek. Aku nggak pengen piscok sekarang.”
Bibirnya mengerucut. “Orang-orang kaya kalian ngak ngerti susahnya hidup, parah bener,” gumamnya pelan, tapi cukup jelas untuk membuat dadaku nyeri.
Seorang pria paruh baya yang duduk tak jauh dariku melirik sekilas, lalu mengangkat bahu seakan berkata, Biasalah, anak kecil begitu.
Tapi, benarkah ini cuma “biasalah”?
Pemandangan seperti ini bukan hal baru di Indonesia. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten dalam data Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (Ribu Jiwa), 2023-2024 menunjukkan bahwa pada Maret 2024, jumlah penduduk miskin mencapai 791,61 ribu orang, menurun 34,5 ribu orang dibandingkan Maret 2023 yakni 826,13 ribu orang. Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional 2024.
Tapi angka-angka ini tidak berbicara tentang wajah anak yang tadi menatapku. Angka-angka ini tak bisa menggambarkan bagaimana ia harus berkeringat di jalanan saat teman sebayanya bermain.
Tak bisa menceritakan bagaimana ia harus menanggung hinaan orang-orang yang tak mau membeli dagangannya, atau ketakutan yang muncul saat ia pulang dengan dagangan tersisa dan orang tuanya bertanya dengan suara keras, “Kenapa nggak laku?”
Sebagian besar dari mereka berasal dari keluarga miskin yang tidak punya pilihan lain. Mereka terpaksa bekerja untuk membantu perekonomian keluarga, sehingga masa kecil mereka terenggut oleh kerasnya kehidupan.
Ada satu kalimat yang sering kudengar “Kalau miskin, jangan punya anak”. Sebuah pernyataan yang tajam dan menusuk, tapi juga menyimpan realitas yang pahit.
Mungkin itu terdengar logis. Mungkin itu benar. Tapi kata-kata itu tak bisa kembali ke masa lalu dan mencegah anak-anak seperti bocah piscok tadi lahir ke dunia yang tak siap menampungnya.
Mereka ada di sini, hidup dalam kemiskinan yang bukan pilihan mereka, mencoba bertahan di dunia yang selalu menyalahkan mereka karena terlahir di dalamnya.
Tapi apakah menyalahkan orang tua mereka adalah solusi? Ataukah ini hanya bentuk keputusasaan kita terhadap kemiskinan yang seperti tidak ada ujungnya?
Mungkin menyalahkan bukanlah solusi. Tapi membiarkan mereka terus berjuang sendirian juga bukan jawaban.
Anak-anak seperti bocah piscok tadi tidak butuh belas kasihan sesaat. Mereka butuh kesempatan. Kesempatan untuk tumbuh tanpa harus mengorbankan masa kecil mereka di jalanan.
Kesempatan untuk bersekolah tanpa dihantui rasa lapar. Kesempatan untuk percaya bahwa dunia tidak selalu sekeras yang mereka alami sekarang.
Apa yang bisa kita lakukan? Mungkin tidak semua dari kita mampu mengubah sistem, tetapi kita bisa mulai dari yang kecil.
Membantu mereka mendapatkan akses ke pendidikan melalui orang tua yang mengerti akan pentingnya pendidikan, mendukung usaha kecil keluarganya, atau bahkan sekadar memberi ruang bagi cerita mereka untuk didengar.
Dan yang terpenting, berhenti melihat mereka sebagai “beban sosial” atau “kesalahan ekonomi.” Mereka bukan angka dalam statistik. Mereka adalah anak-anak yang, jika diberi kesempatan, bisa tumbuh menjadi seseorang yang mengubah dunia.
Karena pada akhirnya, kemiskinan bukan hanya soal kurangnya uang, tapi juga tentang rantai yang terus berulang. Anak-anak yang lahir dalam kondisi sulit, jika tidak diberi kesempatan untuk keluar dari lingkaran ini, akan tumbuh dan mengulang kisah yang sama untuk generasi berikutnya.
Itulah mengapa kita, insan-insan yang kelak akan menjadi ayah dan ibu, harus belajar dari realitas ini. Bukan sekadar menghindari kemiskinan, tapi juga memastikan bahwa jika suatu saat kita memiliki anak, mereka tidak harus menanggung beban yang seharusnya bukan milik mereka.
Mendidik diri sendiri, merencanakan masa depan dengan bijak, dan memahami bahwa menjadi orang tua bukan hanya tentang melahirkan, tapi juga tentang memastikan anak-anak kita punya kehidupan yang lebih baik dari kita.
Saat bedug maghrib berkumandang, aku menyadari satu hal kehidupan mereka tidak akan berubah hanya dalam satu senja. Tapi jika cukup banyak orang yang peduli, mungkin suatu hari nanti, tidak ada lagi bocah yang harus menjual pisang cokelat atau anak anak yang sedang berjuang mencari pundi-pundi rupiah lainnya dengan wajah ketakutan. (*)
Ditulis oleh Khaisya, Zetizens Jurnalistik 2025